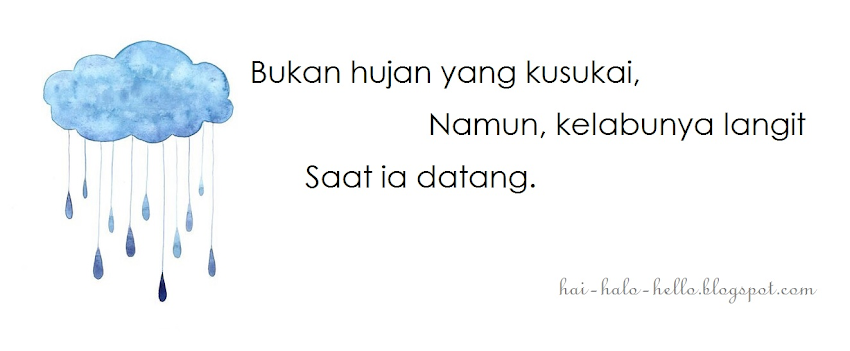Aku masih menunggumu. Kau bilang, kau akan pulang saat senja. Saat matahari menutup tugasnya. Saat langit bersemu malu. Jingga, katamu. Aku masih saja duduk di depan rumah. Dengan secangkir teh dan beberapa biskuit, aku menunggumu hingga langit tak lagi kemerahan. Bulan perlahan menaiki tahtanya. Dan aku tetap saja duduk menunggumu di depan rumah.
Aku masih ingat jelas saat kau pergi. Tak ada bahasa. Tak ada kata. Raut muka dan air mata mengisyaratkan semuanya. Aku terdiam. Tanpa peluk, kau pergi begitu saja. Aku hanya bisa menatap punggungmu hingga kau berlalu. Air mata ini belum kering benar, sayatan luka ini masih menganga lebar. Dan kau pergi. Kau pergi begitu saja!
Senja ini, aku masih menunggumu. Tetap saja tak ada tanda-tanda kehadiranmu. Hingga seorang kawan berlari tergesa-gesa menuju rumah. Aku terlonjak kaget. Ia mengabarkan sebuah mimpi buruk. Mimpi buruk yang tak lagi hanya seutas mimpi. Mimpi buruk ini nyata. Aku marah. Aku menyalahkan Tuhan! Tangis ini berderai. Sang kawan berusaha menenangkanku. Cahaya senja menjadi kelabu. Perlahan, lalu, hilang.
Senja kali ini berwarna jingga terang. Indah sekali. Dan kau pulang. Kau yang selama ini aku tunggu, akhirnya telah pulang. Benar, kau akan pulang saat jingga. Aku menengok ke arah senja. Para dewi telah menyamarkan kepedihan langit dibalik keindahan senja. Hey, bangun! Ini senja kesukaanmu! Bangunlah! Aku memeluk tubuhmu yang membiru. Tak bernafas. Tak bernyawa. Wajahmu basah oleh air mataku. Senja tak lagi berwarna jingga. Ia memucat. Berjalan beriringan dengan ketidak adilan. Senja menjadi kelam.